Oleh Andreas Harsono
Selama dua atau tiga tahun terakhir ini, sejak pulang dari Nieman Fellowship di Harvard, terutama sejak aku ikut dengan majalah Pantau, rasanya aku sering diajak diskusi oleh para wartawan mahasiswa.
Aku kira ini penting sekali karena anak-anak muda inilah yang kelak akan mengisi ruang-ruang redaksi media di kawasan ini. Aku suka diskusi dengan mereka. Aku kira aku juga orang yang berutang pada guru-guruku, dari Arief Budiman hingga George Aditjondro, dari Liek Wilardjo hingga Goenawan Mohamad, dari Seth Mydans hingga Bill Kovach. Aku harus meneruskan tradisi mentor yang penuh kesabaran ini kepada wartawan-wartawan mahasiswa.
Mulanya, aku malu karena tak terbiasa diajak diskusi. Ketika bekerja untuk The Nation, aku praktis jarang berhubungan dengan wartawan disini, selain teman-teman dekat. Kini aku berusaha untuk selalu membuka pintu untuk wartawan mahasiswa. Terkadang untuk bimbingan skripsi mereka. Terkadang diskusi masalah yang aneh-aneh. Terkadang mencari tumpangan menginap di Jakarta. Ada juga yang datang untuk curhat soal kehidupannya. Soal orang tua cerai. Soal putus dengan pacar. Soal kehabisan duit. Macam-macam deh.
Mereka umumnya menyenangkan. Sesekali tapi aku juga jengkel karena kehabisan waktu untuk menulis. Padahal urusan buku benar-benar mendesak. Deadline! Deadline! Deadline! Tapi memang inilah tarik ulur kehidupan. Prinsip, pintu harus senantiasa terbuka.
Aku sering berpikir kelak mereka jadi apa ya? Sebagian dari mereka aku kira akan jadi wartawan. Sebagian mungkin tak mau jadi wartawan. Mudah-mudahan semuanya jadi orang yang bahagia. Tapi menyenangkan sekali bisa berbagi waktu dan pikiran dengan orang-orang muda ini.
Andriyani, Leny Nuzuliyanti dan Muhamad Sulhanudin (dari kiri ke kanan) dari majalah Hayamwuruk, Universitas Diponegoro, Semarang. Mereka lagi bikin liputan "sastra Islami" di Jakarta sekalian mampir di tempatku. Mereka juga ke Bandung dan mampir di rumah Agus Sopian, rekan dari Yayasan Pantau.
Aku sering meledek Udin, Leny dan Andri, agar meliput isu yang lebih mendesak macam pelanggaran hak asasi manusia Acheh atau gerakan kemerdekaan di Papua, ketimbang mencari bahan-bahan diskusi tentang sastra. Udin adalah organizer sebuah kursus jurnalisme sastrawi untuk mahasiswa beberapa bulan lalu (lagi-lagi soal sastra!). Ia organizer yang hebat. Billy Antoro dari IKIP Jakarta tak terlihat dalam foto.
Leny kebetulan menyebutkan umur ayahnya. Ayahnya bekerja di Jakarta dan sempat mengantar Leny ke tempatku. Aku tiba-tiba merasa tua. Umur ayah Leny hanya terpaut empat tahun dengan umurku!
Leny menimbulkan revolusi kecil dalam pikiran. Aku mulai merasa aneh dipanggil, "Mas Andreas" atau "Bang Andreas" atau "Kak Andreas." Umur ayah mereka bisa jadi sebaya dengan umurku? Bukan keberatan --aku lebih suka dipanggil nama saja-- tapi merasa aneh. I am getting older. These kids could be my sons or daughters.
Oh ya, kenapa tak ada yang menyapaku "Ko' Andreas"?
Dalam politik etnik yang pekat ala Orde Baru, bukankah aku bisa dikategorikan sebagai orang "Tionghoa" atau "Cina" atau "non pribumi" dimana sapaan umumnya adalah "koko"?
Tapi lebih tepat lagi, kalau mengingat umur, walau aku bakal merasa lebih aneh, adalah sapaan "giugiu" atau "encek"? Keduanya berarti paman atau oom, masing-masing dalam bahasa Hakka dan Hokkian. "Cek Andreas" atau "Giu Andreas" atau setidaknya "Oom Andreas."
Aneh banget! Tapi politik sapa-menyapa di Jakarta memang aneh banget. Lebih ringan di Amerika sono. Semua sapa nama saja. 
Eva Danayanti, Heni Fuji Astuti, Aulia Marti, Yudi Nopriansyah dan Ahdika Fitrarianto (dari kiri ke kanan) lagi diskusi soal persiapan kursus pers mahasiswa di Lampung dan Pontianak. Eva, Heni dan Yudi dari majalah Teknokra, Universitas Lampung, sedang Lia dan Dika dari Mimbar Untan, Universitas Tanjungpura, Pontianak. Kami mengobrol di apartemenku.
Yudi dan Heni punya ide menarik tentang bikin suatu workshop buat 15 wartawan mahasiswa dari sebagian kampus Jawa, Sumatra dan Kalimantan. Mereka diminta masing-masing menulis esai atau narasi tentang penerbitan mereka, suka duka, sumber keuangan, hambatan dan sebagainya. Ini didiskusikan bersama di Bandar Lampung.
Hasilnya, dijadikan buku tentang pers mahasiswa. Ini ide brilian! Yudi dan Heni suka dengan diskusi di apartemen ini. Apalagi ada Agus Sopian, yang juga menginap di tempatku, "menteror" mereka dengan ide-ide soal jurnalisme dan kemahasiswaan. Temanku, Sven Hansen, redaktur urusan Asia dari Die Tageszeitung, harian Berlin, bersedia membantu secara finansial proyek Lampung dan Pontianak ini dari kantong organisasi Umverteilen!
Ada juga rombongan besar. Pada 20 Mei 2005, aku kedatangan rombongan mahasiswa 20 orang ke apartemenku. Ini tamu terbesar yang pernah aku terima di apartemen kecil dua kamar tidur ini. Para satpam apartemen mengatakan tak pernah ada tamu sebanyak ini di satu unit. Kami sih senang-senang saja. Sayang, aku lagi tak punya banyak penganan.
Kami diskusi singkat saja. Kebetulan Jumat itu aku juga harus mengajar di harian Bisnis Indonesia. Eva Danayanti dan Indarwati Aminuddin, dua kolega Yayasan Pantau, mengajak mereka ikut ke kantor Bisnis. Maka jadilah 20 orang mahasiswa itu ikut mendengarkan cerita di sana. Mereka berkenalan dengan para wartawan Bisnis.
Sesudahnya, kami sempat mejeng bareng. Angkat kaki ramai-ramai. Satu ... dua ... tiga! Cret ... lalu ambruk bareng-bareng.
Gambar ini diusahakan tiga kali karena tak mudah serentak mengangkat kaki. (Dari kiri ke kanan) Anggara Pernando (tabloid Bahana Mahasiswa, Universitas Riau), Wiwit Putri W (majalah Canopy, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang), Subkhan Rama Dani (majalah Dianns, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya), Avanty Nurdiana ("Kavling 10" Universitas Brawijaya), Yanuar Kurniawan (majalah Indikator, Universitas Brawijaya), Nograhany Widhi Koesumawardhani (Canopy), Ahmad Ainur Rohman (Dianns), Hifhzil Aqidi (Republica, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung), Aulia Marti (Mimbar Untan, Universitas Tanjungpura, Pontianak), Tegar Yusuf Putuhena (Manifest, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya), Yusrianti Y.Pontodjaf (Yayasan Pantau), Yoso Mulyawanz (Republica), Ahdika Fitrarianto (Mimbar Untan), Eva Danayanti (Teknokra, Universitas Lampung, magang Yayasan Pantau) dan I Putu Agus Andrian (majalah Indikator).
Sebagian dari mahasiswa ini juga sempat diminta menunggu di ruang direksi Bisnis Indonesia. Geli juga melihat kecanggungan mereka. Coba tebak siapa nama mereka dan dari lembaga mana saja? Oh ya, siapa ya yang paling manis?
31 May 2005
Wartawan Mahasiswa
25 May 2005
The Da Vinci Code: Thriller yang Cerdas*
Oleh Leny Nuzuliyanti**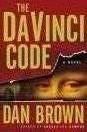
Judul buku : The Da Vinci Code
Penulis : Dan Brown
Penerjemah : Isma B. KOesalamwardi
Jumlah halaman : 641 halaman
Cetakan : I, Juli 2004
Penerbit : Serambi, Jakarta
The Da Vinci Code pertama kali diterbitkan oleh penerbit Double Day penerbit di Amerika. The Da Vinci Code begitu mengguncang sejak awal kemunculannya pada bulan April 2003. Hingga kini, karya ini telah diterjemahkan lebih dari 40 bahasa. Per 20 Maret 2005, angka penjualannya telah mencapai 18 juta kopi.
Di Indonesia, The Da Vinci Code diterbitkan oleh Penerbit Serambi. Dirilis pertama kali pada Juni 2004. Dalam waktu 10 bulan, telah mengalami 15 kali cetak ulang dan telah terjual sebanyak 70.000 eksemplar. Dalam versi Indonesia, The Da Vinci Code terbit dalam dua edisi: edisi soft cover dengan kertas koran seharga Rp. 74.900,00 per eksemplar, dan edisi hard cover dengan kertas HVS seharga Rp. 99.000,00. Angka penjualan tersebut begitu fantastis untuk ukuran Indonesia. Barangkali hanya bisa ditandingi oleh Harry Potter tulisan J.K. Rowling dan Jakarta Undercover tulisan Moamar Emka.
The Da Vinci Code mengusung tema yang akan menikam jantung keimanan Katholik tentang pernikahan rahasia Yesus Kristus dengan Maria Magdalena dan keturunan mereka yang masih bertahan hidup hingga zaman modern ini.
Cerita diawali dengan petualangan Robert Langdon, seorang profesor simbologi agama dari Havard University yang terjebak dalam konspirasi yang diciptakan oleh Sir Leigh Teabing, sejarawan Grail Inggris, selama enam bulan sebelumnya.
Konspirasi itu berawal ketika Sir Leigh Teabing mendengar kasak-kusuk bahwa Vatikan akan mencabut dukungan kepada Opus Dei, gereja Katholik konservatif. Dengan menyamar sebagai Guru, Sir Leigh Teabing menawarkan kekuasaan pada Uskup Aringarosa, pemimpin Opus Dei, berupa Dokumen Sangreal. Dokumen itu hanya bisa dibuka dengan Batu Pengunci.
Uskup Aringarosa menyuruh Silas, anak asuhnya, untuk mencari Batu Pengunci di Paris. Informasi tentang Batu Pengunci didapat Silas dari anggota Priory of Sion, yang terdiri dari seorang grand master atau pemimpin dan tiga orang senechaux atau pengawal. Setelah mendapat informasi yang diinginkannya, Silas membunuh keempatnya. Namun Silas kecele karena ternyata dia tidak mendapati Batu Pengunci yang dicarinya di Gereja Saint Sulpice.
Grand master Priory of Sion adalah Jacques Saunaire. Jacques Saunaire sendiri sehari-hari bekerja sebagai kurator di Museum Louvre. Priory of Sion adalah sebuah persaudaraan kuno yang bersetia menjaga kemurnian ajaran agama Kristen yang tertuang dalam sekumpulan dokumen penting –Sangreal, Sangraal, Angreal, atau Holy Grail- tanpa perduli berapa lama waktu yang mereka butuhkan.
Sebelum mati di tangan Silas di Museum Louvre, Jacques Saunaire meninggalkan kode agar dalam penyidikan kematiannya, polisi melibatkan Sophie Neveu, cucunya, yang bekerja di Departemen Kriptologi. Di sinilah keterlibatan Robert Langdon bermula. Dia dicurigai sebagai pembunuh Jacques Saunaire karena Jacques Saunaire menulis namanya sebagai bagian dari kode di samping mayatnya. Selain itu, nama Robert Langdon juga tercantum dalam daily planner Jacques Saunaire: keduanya ada janji untuk minum pada waktu terbunuhnya Jacques Saunaire.
Sophie Neveu tahu bahwa pelibatan Robert Langdon oleh Bezu Fache, kapten Polisi Pengadilan Perancis, merupakan jebakan untuk menyelamatkan reputasinya sendiri. Sophie Neveu merasa bahwa ketika kakeknya mencantumkan nama Robert Langdon, bukannya tanpa tujuan. Berikutnya, Robert Langdon memang banyak membantu Sophie Neveu memecahkan kesulitan yang dihadapi Sophie Neveu, sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang ahli simbologi agama.
Sophie Neveu lantas menyelamatkan Robert Langdon dari cengkeraman Bezu Fache. Akibatnya, Robert Langdon dan Sophie Neveu menjadi buronan begitu keluar dari Museum Louvre. Bezu Fache yang melibatkan Interpol menyulitkan pelarian Sophie Neveu dan Robert Langdon.
Jacques Saunaire mewariskan sesuatu untuk Sophie Neveu di Bank Penyimpanan Zurich. Warisan Jacques Saunaire berupa sebuah kotak kayu berukir mawar yang berisi cryptex. Pelarian mereka dari Bank Penyimpanan Zurich dibantu Andre Vernet, direktur bank itu yang sekaligus kawan baik Jacques Saunaire.
Perjalanan mereka berlanjut ke Puri Villette, kediaman Sir Leigh Teabing. Sir Leigh Teabing alias Guru sudah memersiapkan segalanya. Dia memerintah Silas mengincar cryptex yang dibawa Robert Langdon dan Sophie Neveu yang diduganya sebagai Dokumen Sangreal. Keadaan menjadi runyam ketika Silas berusaha merebut cryptex itu tanpa tahu bahwa Guru yang selama ini menyembunyikan identitasnya sebenarnya adalah Sir Leigh Teabing.
Sir Leigh Teabing membantu Sophie Neveu dan Robert Langdon melarikan diri karena polisi berhasil mengejar keduanya hingga ke rumahnya. Mereka meninggalkan Perancis dengan pesawat pribadi Sir Leigh Teabing, Elizabeth, dari bandara Bourget. Tujuan mereka adalah Bandara Biggin, Inggris.
Dalam perjalanan itu, terkuaklah penyebab rusaknya hubungan Sophie Neveu dan kakeknya. Sepuluh tahun silam, Sophie Neveu menyaksikan upacara Hieros Gamos, ritual pernikahan suci, yang menobatkan Jacques Saunaire sebagai grand master Priory of Sion. Sophie Neveu tak tahu apapun tentang Hieros Gamos. Di mata Sophie Neveu, apa yang dilihatnya adalah sebuah sebuah upacara seks. Sejak saat itu Sophie Neveu tak mau lagi berhubungan dengannya. Sophie Neveu menyesal setelah tahu semuanya dari penjelasan Robert Langdon.
Di Bandara Biggin, Bezu Fache sudah bersiap menyambut rombongan Sir Leigh Teabing dengan bantuan polisi setempat. Sir Leigh Teabing berhasil menyelamatkan Sophie Neveu, Robert Langdon, dan Silas yang disekapnya dari polisi dengan bantuan Remy Lagaludec, pembantunya.
Mereka menuju Gereja Kuil yang ditengarai menyimpan kunci pembuka cryptex itu. Kekacauan terjadi ketika Remy membebaskan Silas dan bersama-sama berpura-pura menyandera Sir Leigh Teabing untuk mendapatkan cryptex yang masih berada di tangan Sophie Neveu dan Robert Langdon.
Setelah cryptex itu berpindah tangan, Sophie Neveu dan Robert Langdon menuju perpustakaan King’s College untuk melakukan riset tentang Dokumen Sangreal. Sedangkan Remy Lagaludec, Silas, dan Sir Leigh Teabing menuju St. James Park dengan limosin Sir Leigh Teabing. Di sana Silas harus turun dan beristirahat di markas Opus Dei London.
Remy Lagaludec membebaskan Sir Leigh Teabing yang tak lain adalah Guru. Sir Leigh Teabing lantas membunuh Remy Lagaludec dengan meracun minumannya karena Remy Lagaludec lah satu-satunya yang mengetahui identitasnya sebenarnya. Sir Leigh Teabing mengambil cryptex yang diduganya sebagai Dokumen Sangreal dari Remy Lagaludec dan mencari kunci pembukanya di dalam Wesminister Abbey, salah satu katredal paling terkenal di Inggris Raya.
Polisi dan Uskup Aringarosa mengejar Silas di markas Opus Dei London. Uskup Aringarosa sudah tahu semuanya –bahwa dia dan Silas hanya diperalat oleh Guru alias Sir Leigh Teabing- dari Kapten Bezu Fache. Penyadapan yang dilakukan Remy Lagaludec atas perintah Sir Leigh Teabing di loteng Puri Villette ditemukan Letnan Collet menyediakan banyak informasi tentang konspirasi Sir Leigh Teabing. Saat menghindari polisi, tanpa sepengetahuan Silas, pelurunya bersarang dalam tubuh Uskup Aringarosa.
Di Wesminister Abbey, Sir Leigh Teabing tak menemukan kata kunci pembuka cryptex yang dibawanya. Melihat kedatangan Sophie Neveu dan Robert Langdon, Sir Leigh Teabing berpikir untuk mengalihkan perhatian mereka ke Chapter House, sebuah gazebo segi delapan yang dulu biasa dipakai sebagai ruang sidang.
Di Chapter House, ketiganya bertemu. Sophie Neveu dan Robert Langdon terkejut mengetahui bahwa penculikan Sir Leigh Teabing adalah rekayasanya sendiri. Sir Leigh Teabing menyandera Sophie Neveu. Bagaimanapun juga, Sir Leigh Teabing masih membutuhkan bantuan Robert Langdon untuk membuka cryptex itu. Pun Robert Langdon bisa membuka cryptex itu, Robert Langdon memilih membiarkan cryptex itu pecah dan menyimpan sendiri papirus di dalamnya. Polisi yang mendapat laporan dari penjaga Wesminister Abbey akan kedatangan Sir Leigh Teabing menangkap Sir Leigh Teabing di Chapter House.
Sophie Neveu dan Robert Langdon meneruskan perjalanan menuju Kapel Rosslyn, 7 mil ke arah selatan dari Eidenburg, sesuai petunjuk yang terdapat dalam papirus. Mungkin di sana terletak Dokumen Sangreal. Sophie Neveu merasa mengenali gereja itu. Kakeknya pernah membawanya ke tempat itu semasa masih kecil. Sophie Neveu menemui pimpinan Kapel Rosslyn yang tak lain adalah neneknya.
Rahasia kehidupan Sophie Neveu terkuak. Sophie Neveu sebenarnya adalah keturunan langsung dari keluarga Merovingram, keturunan langsung Yesus Kristus dan Maria Magdalena. Kecelakaan mobil yang menewaskan kedua orang tua Sophie Neveu ditengarai telah direncanakan –mungkin oleh Vatikan yang memang selalu berusaha menghabisi keturunan Yesus Kristus – Maria Magdalena. Untuk melindungi cucunya, Jacques Saunaire memutuskan untuk hidup di tempat terpisah dari istrinya. Jacques Saunaire mengasuh Sophie Neveu, sementara istrinya mengasuh adik Sophie Neveu. Keduanya hanya bertemu setiap upacara Hieros Gamos pada setiap awal musim semi di bulan Maret.
Robert Langdon kembali ke Perancis dan meninggalkan Sophie Neveu di Eidenburg untuk sementara waktu tinggal bersama keluarganya yang baru saja berkumpul setelah sekian lama tercerai berai. Beberapa hari setelah istirahatnya cukup, Robert Langdon merasa bahwa dia tahu dimana Dokumen Sangreal sesungguhnya tersembunyi. Diikutinya petunjuk dalam papirus peninggalan Jacques Sauniere. Perjalanan Robert Langdon berakhir pada Le Pyramid Inversee di depan Museum Louvre. Robert Langdon berlutut merasai suara Maria Magdalena karena sesungguhnya pencarian Dokumen Sangreal adalah keinginan untuk berlutut di depan tulang belulang “perempuan suci yang terbuang”.
TIDAK sedikit kritik yang dialamatkan pada Dan Brown selaku penulis The Da Vinci Code maupun Doubleday selaku penerbit. Brown membuka diskusi terbuka tentang The Da Vinci Code melalui website-nya, www.danbrown.com. Menanggapi kritik yang menghujaninya, Brown hanya berkomentar, “It’s a work of fiction.” Sementara penerbit Double Day hanya memberi keterangan bahwa Brown sedang berkonsentrasi dengan buku terbarunya.
Vatikan sendiri, setelah sekian lama berdiam, akhirnya mengeluarkan tanggapan. Cardinal Tarciso Bertone dari Genoa dalam Vatican Radio seperti dikutip Washinton Post, 20 Maret 2005, menyatakan bahwa tak seorangpun seharusnya membaca The Da Vinci Code dan sudah waktunya toko buku Katholik berhenti menjual buku itu.
Sekurang-kurangnya 20 buku telah ditulis untuk menangkis apa yang dikatakan Brown dalam The Da Vinci Code. Tiga diantaranya adalah The Da Vinci Hoax tulisan Carl E. Olson, seorang editor majalah Envoy, dan Sandra Miesel, seorang ahli abad pertengahan dan mantan jurnalis Katolik; Breaking The Da Vinci Code tulisan ... (CEK!); dan Fakta dan Fiksi dalam The Da Vinci Code tulisan ... (CEK!). Beberapa gereja sampai membuat brosur dan memberikan studi pendampingan bagi mereka yang telah membaca The Da Vinci Code dan mempertanyakan keimanannya. Hal ini ditempuh karena ternyata tak sedikit orang yang merasa keimanannya terguncang setelah membaca The Da Vinci Code.
Selain materi, referensi yang digunakan oleh Brown dalam The Da Vinci Code juga diragukan kredibilitasnya. Sebagai contoh Holy Blood, Holy Graill tulisan Michale Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln yang dikenal sebagai penulis fiksi yang senang berfantasi dan menghubung-hubungkan Maria Magdalena, kaum Merovingian, kaum Kathar, legenda “Piala Suci” (Holy Grail), dan sebagainya. Buku-buku lain seperti The Gnostic Gospel (Elain Pagels); The Templar Revelation: Secret Guardians of the True Identity of Christ (Lyn Picknett & Clive Prince), The Godess In The Gospels: Reclaiming The Sacred Feminine dan The Woman with Alabaster Jar: Mary Magdalen and the Holy Grail (Margaret Starbird) juga dianggap tidak valid. Brown pada halaman pertama The Da Vinci Code mencantumkan sumber-sumber tersebut sebagai “fakta”.
Sebenarnya, The Da Vinci Code bukanlah satu-satunya buku yang menyerang sensi-sendi iman Khatolik. Jesus Christ Superstar yang digarap oleh Andrew Lioyd Webber bercerita tentang affair Yesus dan Maria Magdalena. Demikian halnya The Last Temptation of Christ yang disutradarai Martin Scorsese. Sayangnya, baik Jesus Christ Superstar maupun The Last Temptation of Christ tidak begitu fenomenal seperti The Da Vinci Code.
Saat ini, Penerbit Serambi tengah mempersiapkan The Da Vinci Code dalam edisi bergambar. The Da Vinci Code versi ilustrasi itu akan dirilis bersamaan dengan karya Brown yang lain, Digital Forstress yang diterjemahkan menjadi Titik Muslihat, pada Juli 2005.
The Da Vinci Code tak luput dari perhatian Hollywood. Saat ini sedang digarap oleh Columbia-Tristars Pictures. The Da Vinci Code versi film disutradarai oleh Ron Howard yang juga pernah menyutradarai A Beautiful Mind dam dibintangi oleh Tom Hanks. Film ini baru akan dirilis pada November 2005.
*Dipublikasikan di Hawe Pos, edisi 12/Mei/2005, dalam rubrik Pustaka.
**Pemimpin Perusahaan LPM Hayamwuruk
23 May 2005
Buat Andreas Harsono,
Saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya dalam mengenal Anda. Saya belum begitu lama mengenal Anda. Pertama kali kontak dengan Anda saat Hayamwuruk akan mengadakan workshop jurnalisme sastrawi, sekitar bulan Oktober 2004.
Saat itu saya mengenal Anda melalui tulisan-tulisan Anda di majalah Pantau. Diam-diam saya juga bergabung di milis Pantau Komunitas. Meski saya hanya jadi pendengar setia. Sekilas saya menarik kesimpulan bahwa anda adalah orang yang keras kepala. Terlihat dari pemikiran-pemikiran yang keras. Kok ada ya orang seperti ini?, pikir saya saat itu.
Saya mengenal majalah Pantau dari para senior di Hayamwuruk. Majalah itu sering kami jadikan bahan diskusi. Kami pun kemudian sepakat untuk "meniru" teknik penulisan Pantau. Oleh karenanya, mulai edisi terakhir, Hayamwuruk bermigrasi dari format ala Tempo menjadi ala Pantau.
Kami menerima kabar gembira saat salah seorang pengelola Hayamwuruk mendapat kesempatan untuk mengikuti kursus jurnalisme sastrawi di Pantau. Itu merupakan keenam kalinya Pantau mengadakan kursus serupa.Ia adalah Hendra Wibawa. Ia banyak bercerita tentang aktivitasnya selama mengikuti kursus.
Dalam diskusi kecil muncul pertanyaan. Kenapa pelatihan seperti itu tidak diadakan khusus untuk mahasiswa, bukankah ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk pers mahasiswa? Alasan tersebut yang melatarbelakangi keinginan kami untuk mengadakan kursus jurnalisme sastrawi bagi pers mahasiswa nasional.
BULAN Januari, awal tahun lalu, akhirnya saya bisa bertemu Anda. Tepatnya saat Pantau mengadakan kursus jurnalisme sastrawi yang ke tujuh. Itu pertama kalinya saya bertemu Anda. Saya masih agak canggung meski Anda bersikap amat ramah sebagai orang yang baru kenal. Maklum orang Jawa, sok malu-malu padahal mau, hik hik, kasihan deh saya.
Saya terlibat perbincangan dengan Anda saat berkunjung ke apartemen. Wuah, seketika itu juga anggapan-anggapan saya sebelumnya runtuh. Masak sih Andreas orang yang sangat keras kepala atau angkuh. Justru sebaliknya, apa yang saya dapati dia sangat rendah hati. Ya, kalau bukan karena rendah hati itu, mana mungkin ia mau ngobrol dengan orang awam seperti diriku. Bukankah dia adalah seorang wartawan yang hebat. Yang tak hanya di kenal dari Sabang sampai Merauke, tapi juga di berbagai belahan bangsa lain.
Kekagetan-kekagetan saya tak berhenti di situ. Dia ternyata mau mendengarkan pandangan dari orang lain. Bahkan untuk sekadar keluh kesah. Tak hanya itu, saya tak habis pikir, dia juga tak segan untuk minta komentar dari orang yang sangat awam sekalipun seperti saya. Seperti peristiwa yang terjadi pertengahan bulan Mei belum lama ini, saat saya dan kedua teman saya menginap di tempat Anda. Saat itu Anda menyodorkan naskah berbahasa inggris dan meminta saya untuk mengomentarinya. Dalam benak saya, "lha, po wis edan (apa aku dah gila), aku ngasih komentar untuk tulisan Andreas".
Bulan Februari lalu, selama tanggal 7-12, pelatihan yang direnacakan dilaksanakan di Semarang. Dalam kesempatan itu, Agus Sopian dan Linda Christanty, menjadi instruktur. Ditambah lagi Juwendara, salah seorang alumni kursus jurnalisme sastrawi di Pantau.
Agus Sopian adalah orang yang amat menyenangkan. Dia tak hanya pinter menulis, tapi juga mahir ngebanyol. Saya teringat saat salah seorang peserta perempuan dijebak pertanyaan berapa ukuran bra-nya. Perempuan itu tersipu malu. mukanya merah tak karuan. Tapi toh akhirnya ia menjawab juga. Setelah mendapat jawaban itu, Kang Agus baru memberi tahu kalau apa yang dilakukanya itu adalah trik untuk mengorek informsi dari yang bersifat umum sampai yang sangat bersifat personal. Beberapa orang yang tahu kemudian pun tak mampu menahan tawa.
Linda Christanty juga mempunyai kepribadian yang tak kalah menyenangkan. Dia lincah dalam menyampaikan materi. Salah seorang peserta bilang kalau mbak Linda orangnya manis. Sampai-sampai dia bertanya tentang statusnya saat itu. Hanya saja, pada acara itu dia kurang banyak bergaul dengan peserta. Ia banyak mengurung di kamar seusai menyampaikan materi di kelas. Katanya, ia sedang mempersiapkan 'kencannya' dengan Japan Foundation gara-gara cerpennya "Kuda Panggang Mario Pinto" itu. Pantas saja ia pulang satu hari lebih awal.
Dari situ saya banyak mengenal karakter orang-orang Pantau. Mas Andreas, Kang Agus, mbak Linda. Anda semua orang yang amat menyenagkan.
Dalam perbincangan dengan Ikram, awal bulan Mei lalu saat ketemu di Bandung, ia mengaku terkejut saat tulisannya dikomentari oleh Mas Andre."wuah, gue senang banget tulisan gue dikomentari sama Andreas Harsono", tuturnya. Di atas dipan tempat tiduranya saya menemukan dua lembar kertas ditempel di dinding kamar kos-kosnya yang tak terlalu luas itu."itu adalah komentar dari kang Agus, saat aku nulis di Boul (boulevard, pers mahasiswa ITB)", sahutnya.
Saya coba menangkap raut ceria di wajah Ikram. Ada apa dengan komentar Andreas, ada apa juga dengan komentar Agus Sopian, sampai-sampai Ikram memajangnya di atas tempat tidurnya. Apakah itu berlebihan?Saya mencoba menjawab dengan pengakuan sama seperti yang saya alami. Kenapa juga saya merasa begitu bangga bisa kenal orang-orang Pantau itu?
Dalam perbincangan kecil dengan Ikram, saya menemukan jawaban. "karena mereka sangat memperhatikan kami". Ikram tak menolak. Orang-orang seperti Andreas, Kang Agus, ini lah yang masih mau meluangkan waktu untuk memperhatikan perkembangan para calon wartawan, pers mahasiswa ini dan media Indonesia pada umumnya.
*Usai liputan majalah Hayamwuruk, Bandung-Jakarta, 7-14 Mei 2005
21 May 2005
Menyoal Eksistensi Menwa
Tanggapan untuk Ikram di Boulevard, Lembaga Pers Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB),
Saya pengen urun rembuk (usul pemikiran) dari komentar yangdisampaikan oleh Ikram mengenai keberadaan Menwa di kampusnya ITB.Saya akan menyampaikan komentar saya dari apa yang saya temukan diUndip.Hayamwuruk pernah menulis tentang Resimen Mahasiswa (Menwa) padaedisi I TH X /1995. Tulisan tersebut dimuat dalam rubrik komentardengan judul "Keraguan di Sekitar Keberadaan Menwa".Walhasil, setelah pemberitaan itu kantor redaksi Hayamwuruk dilimparibatu oleh orang yang tidak dikenal. Batu itu dibungkus dengan kertasbertuliskan 'untuk Hayamwuruk'.Waktu itu Menwa memang masih lekat dengan seragam Loreng ala militerdan masih diijinkan untuk membawa pistol dan senjata tajam.Keberadaannya membuat mereka tampak eksklusif.Di kampus mereka menjadi tangan kanan rektor untuk memonitoraktivitas gerakan mahasiswa. Posisi ini sering membuat merekaberlawanan dengan kawan mahasiswa yang lain. Tak jarang bentrok Menwa-mahasiswa dalam aksi demonstrasi terjadi.Hal ini membuat keberadaan Menwa makin terpojok. Mereka dikucilkandari komunitas mahasiswa yang lain karena tidak satu aliran dan satugerakan.Beberapa kali dalam sejarah, Menwa melakuakan pembenahan posisi. Padamulanya wadah ini untuk menampung mahasiswa yang tertarik dengan olahkeprajuritan. Keberadaan mereka diperkuat dengan SKB (Surat KeputusanBersama) tiga menteri-Mendagri, Menhankam, dan Mendikbud. Dalamperjalanannya Menwa semakin menunjukkan peran gandannya. Sikapekskulisif tersebut menjadikan anggota menwa superior dan over acting.Setelah reformasi bergulir, Menwa mulai menata kembali keberadaannyadalam kancah aktivitas mahasiswa di kampus. Menwa yang sebelum masareformasi langsung di bawah komando Pangdam sekarang dikendalikanoleh masing-masing rektor. Posisinya sekarang sama dengan unit-unitkegiatan mahasiswa lain di tingkat universitas.Perubahan tersebut terpaksa harus dilakukan bila tidak protes kerasuntuk membubarkan Menwa akan semakin memerahkan telinga mereka.Gambaran di atas adalah potret Menwa zaman doeloe, Menwa di Undipsekarang sudah mulai bisa menempatkan posisinya. Mulai dari seragammereka. Di kampus mereka menggunakan seragam PDH (Pakian DinasHarian). Warnanya coklat muda, saya menyebutnya `krem'. Lebih miripseperti seragam dinas pegawai Pemda.Di luar kampus, misalnya dalam kegiatan latihan mereka di lapangan,mereka mengenakan seragam PDL (Pakian Dinas Lapangan). Warnanya hijautua, seperti seragam TNI. Memang seragam TNI, karena sebagian jugamemakianya dari pakaian bekas TNI yang mereka dapat dari pasaran.Saat ini, kegiatan mereka di kampus akan ditemuai dalam berbagaiacara seremonial universitas. Seperti dalam prosesi wisuda, upacarabendera memperingati hari-hari nasional dan acara seremonial lainnya.Peran dan fungsi ganda sebagai spionase TNI maupun rektor sudah sulitsekali ditemukan. Bahkan sulit sekali untuk membuktikannya.Dalam aktivitas kemahasiswaan di Kampus sekarang, mereka jugadilibatkan. Sebagai contoh dalam kegiatan Pemilihan Umum RayaUniversitas, mereka juga dilibatkan dalam struktur dewan pengawas.Sama seperti unit-unit kegiatan mahasiswa lain. Mereka terlihat bisamembaur dengan komunitas mahasiswa lain.Dengan keluwesannya, Menwa di Undip agaknya sudah mulai bisaditerima. Buktinya sudah jarang yang mempermasalahkan. Mereka jugasama seperti mahasiswa yang lain.Kalau mahasiswa ikut UKM, mereka bisa berharap agar bisa mendapatkeahlian tertentu sesuai yang mereka inginkan. Sama halnya denganmahasiswa yang masuk Menwa. Mereka yang masuk Menwa ingin tahutentang pengetahuan bela Negara. Atau sekadar ingin belajar baris-berbaris, ingin berlatih menembak, atau ingin tahu tentang duniamiliter. Tapi itu hak mereka juga khan? Termasuk apakah mereka jugapengagum sosok TNI juga sah-sah saja. Bukankah kita juga secaraterang-terangan juga memposisikan diri sebagai orang pers? Dalam halini juga pengagum sosok `jurnalis'.Semua punya porsi yang sama. UKM adalah tempat untuk berproses,tempat untuk menekuni bidang keahliannnya masing-masing. Cumapermasalahnnya, UKM juga mahasiswa. Punya idealisme, punya sense ofintellectual. Tapi perlu diingat bahwa mahasiswa juga manusia, punyarasa, punya keinginan, he2…Bagi saya yang penting selama masih dalam batas kewajaran it's OK.Menwa adalah Menwa, bukan militer. Mereka sama seperti yang lain,kumpulan mahasiswa yang menekuni bidang yang ia geluti.Namun bila sudah diluar batas kewajaran, bahkan bila Menwa sekarangtidak ada bedanya dengan Menwa zaman orde baru, itu baru perludipertanyakan. Bagaimana?
Tak Ada Sastra Islami
Tanggapan untuk Nouval,
>>>>masalah kasih sayang khan masalah yang memang sangat sedangdibutuhkan dalam pola kerja aktifis pers, biar menjadi siraman rohaniyang membuat jiwa nggak kering dan bisa selalau segarOke, sepakat dech. Tapi komentar saya sebelumnya, soal `biro jodoh'untuk wartawan itu cuma untuk mencairkan suasana aja. Gitu loh.
>>>>Btw, kalau masalah orang mau menonjolkan masalah keislaman atauagama apapun itu.. (kebetulan yang dibahas disini perihal FLP yangbasisnya Islam) itu toch menurut saya merupakan sebuah usaha untukmemberikan nyawa kepada tulisan yang dia buatOke, untuk sekedar memberikan 'ruh' tulisan saya masih bisa tolerir.Namun bila kemudian 'simbol-simbol agama' itu muncul secara vulgardan kehadirannya justru mengganggu kebebasan ekspresi si penulis ituyang saya tidak setuju. Lebih tidak sepakat lagi, seperti yang sudahsaya sampaikan sebelumnya, agama dijadikan sebagai motivasi menulis.Jadinya, penulis berdakwah dalam tulisan.Dah, sekarang anda bisa lihat, tema-tema yang diangkat oleh parapenulis fiksi islami, khususnya para penulis FLP, ya itu-itu saja.Apa berani mereka mengangkat tema yang tidak islami? (batasan inisebenarnya masih bisa diperdebatkan. Apa benar karya Ayu Utami dkktidak mengandung nilai-nilai Islam. Batasannya apa?).Jadinya kreativitas mereka terkungkung oleh standar yang mereka patoksendiri. Mereka tidak berani berpikir bebas, akhirnya kayak katakdalam tempurung. duh, kasihan ya.. mau begini, beitu.. kuatir haramdilaknat oleh tuhan. ya akhirnya karya para penulis turun-temurun yasama. Para penulis pemula mengekor penulis kawakan yang sebenarnyajuga tidak cukup bagus.Menjadikan agama sebagai standar ganda dalam sastra amat lemah bilakita lihat dari kacamata estetika sastra. Ini mirip ketika parapolitikus menggunakan agama sebagai kendaraan politiknya, apa yangterjadi? Ayat-ayat agama hanya digunakan untuk tujuan pendekpolitiknya.Dalam kesusasteraan Inggris seorang penyair "William Blake" pernahmelakukan kecerobohan serupa dalam puisinya yang berjudul "TheChimney Sweeper". Puisi ini bercerita tentang masuknya era revolusiindustri di Inggris. Blake menggunakan nama "Angel", sebagai simboltuhan untuk membangkitkan kesadaran palsu bahwa seolah-olah revolusiindustri itu perintah yang datang dari tuhan. Kesadaran palsu ituhanya sebuah extacy, untuk menenangkan gejolak sesaat, bukan datangdari akal sehat. Padahal dalam kenyataannya banyak anak di bawah umurdipekerjakan, budaya lokal masyarakat menjadi terjajah. Oke sayatunjukkan satu bait dimana Blake menggunakan kesadaran palsu itu:Then naked & white, all their bags left behind,They rise upon clouds and sport in the wind.And the Angel told Tom if he'd be a good boy,He'd have God for his father & never want joyDalam karya fiksi islami, penulis menggunakan simbol-simbol agamasecara vulgar untuk membangkitkan kesadaran `jiwa' para pembaca. Nah,apakah pembaca menginginkan hal itu. Jadi jangan salah bila karyamereka hanya dikonsumsi oleh kalangan mereka sendiri. Ya, kayak orangonani itu.FLP Semarang pernah menghadirkan Prie GS, budayawan dan Sastrawan,dalam acara bedah novel "ayat-ayat cinta" karya Habiburrahman (kangabi). Penulis juga hadir di situ. Prie menantang pada para penulisFLP, berani gak karya Anda dibaca oleh orang diluar komunitas Anda?(itu untuk membuktikan bahwa di mata pembaca saja mereka sudahmengkotak-kotakkan).Bila anda telah membaca, novel `Ayat-ayat cinta' juga masih lemahdari segi estetikanya (tema, karakter, plot, setting, dll). Nuansaislami masih teramat kental. Penulis belum bisa melepaskan identitasdia ketika menulis. Endingnya juga `determinstik' (yaitu suatukejadian tidak dibangun oleh alur, tapi oleh peristiwa lain yangtidak ada di alur. Bisa dikatakan muncul secara tiba-tiba). Anda maubahas karya ini lebih lanjut, oke saya layani. Namun juga perludipertimbangkan apakah semua anggota milis tertarik dengan bahasanini.>>>>Memberikan "nyawa", merupakan sisi spiritual pada sebuah tulisan,menurut saya memerlukan proses dan juga waktu yang bisa panjang bisajuga pendek, tergantung pada kualitas individunya. Kalau dulu, OomPram perlu harus keluar masuk penjara dulu, baru bisa mendapatkancara bagaimana bisa mebuat tulisannya sedemikian "hidup".Betul menulis memerlukan proses. Pada gilirannya nanti, bila penulispemula seperti di FLP mau berproses, kelak juga akan mampu menulislebih baik. Saya akui ada beberapa karya HTR (Helvi Tiana Rosa) yangsaya suka, karena disitu pesan islamnya tidak vulgar. Tapi sebagianlagi karya HTR dan Asma Nadia, adiknya tuh yang karyanya pacaran2melulu, masih terjebak pada kerangka dakwah. Dia menyampaikan pesanagama secara vulgar biar pembaca memakai jilbab kek, tidak berpacaransebelum menikah kek, dan kek-kek yang lain.Apa yang terjadi pada Pram adalah sebuah kebetulan. Seperti yang sayakatakan sastra ada dua katagori yaitu realis dan non realis. Pramdalam beberapa karyanya menceritakan pengalamannya. Ini sangat baguskarena ia mengalaminya sendiri, cara seperti ini mirip modelImmersion Reporting karena si penulis seolah-olah terlibat dalamtulisan.Tapi bukan berarti untuk membuat tulisan yang dahsyat, penulis harusmenagalaminya sendiri. Proses kreatif para menulis bermacam-macam.Linda Christanty, bisa bercerita tentang kehidupan militer dalamcerpennya Kuda Panggang, eh "Kuda Terbang Mario Pinto" dengan cukupmemwawancarai orang saja. Linda bukan militer, bahkan dia mungkin takpernah ikut berperang.Bila Anda belajar teknik menulis jurnalisme sastra, resep menulismbak Linda itu diajarkan. Jurnalisme sastrawi dan gaya sastra lainnyamampu merekonstruksi sebuah kejadian yang melaporkan bak sebuahhidden kamera yang menyorot peristiwa yang dilaporkan itu. Tulisanmenjadi asik untuk dibaca, dan tidak terkesan menggurui karena apayang disampaikan adalah detail-deteil fakta. Menulis fiksi pundemikian. Detail-detail bisa digunakan untuk menjelaskan imajinasipenulis.Ya, proses penulis bermacem-macem. Biarlah tak usah dibatasi, apakahdia mau nonton VCD, mau bakar-bakar kemenyan, ya sah-sah saja. MisalAyu Utami atau Djenar Mahesa Ayu. Bisa jadi mereka bisa membuatadegan yang heboh itu karena menonton VCD cabul. silakan, takmasalah. Toh dia menyampaikan memang faktanya demikian, dan pembacajuga tidak merasakan kesan bahwa karya mereka cabul (kecuali orangFLP yang melihat Sastra dari kacamata islami).Bila kita memahami bahwa sastra adalah milik semua umat, bahwa sastraitu memiliki estetika, maka tak akan muncul sastra islami (islami danislam berbeda lho). Jangan campur adukkan kepentingan dalam sastra,karena hanya akan merusak keindahan sastra itu sendiri.
Jalan Hidup Seorang Penulis*
Berhenti dari mengajar, Triyanto Triwikromo memilih jadi penulis
Oleh Sundari Dewi Ningrum**
Meski hari mulai gelap, aktivitas perkuliahan masih berlangsung di kampus Sastra Universitas Diponegoro. Bahkan tak kalah padat bila dibanding pagi dan siang harinya. Beberapa mahasiswa berkerumun di teras-teras depan ruangan. Pemandangan yang sama juga terlihat di panggung timur. Berbagai jenis mobil berderet di halaman parkir sebelah timur dan di tepi-tepi jalan depan kampus, turut meramaikan suasana. Tak asing lagi, seperti biasanya, sore itu kampus Sastra digunakan untuk kuliah mahasiswa program ekstensi dan pasca sarjana.
Dari Ruang Sidang, beberapa mahasiswa pasca sarjana berhamburan keluar ruangan. Saya menghampiri satu diantaranya. Ia adalah Triyanto Triwikromo, cerpenis cum wartawan yang baru melanjutkan studinya di Magister Ilmu Susastra di fakultas ini. Kami kemudian berbincang-bincang di bangku depan ruang Jurusan Sastra Inggris.
TRIYANTO Triwikromo adalah nama yang tengah bersinar dalam dunia penulisan fiksi, khususnya sebagai penulis cerpen. Dalam kumpulan cerpen Anak-Anak Mengasah Pisau yang dirilis tahun 2003, Darmanto Jatman, budayawan dan dosen FISIP Undip, memberi catatan pada endorsemen bahwa cerpen Triyanto merupakan dekonstruksi terhadap ideologi keindahan cerpen konvensinal.
Tak ketinggalan, Prof.Dr.Th.Sri Rahayu Prihatmi, Dekan Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, juga mencatat bahwa ketidakpastian cerita rekaan Triyanto ini justru merupakan salah satu ciri cerita rekaan yang menggunakan modus fantastik, satu cara ungkap yang merongrong tradisi Sastra yang mapan. Isinya pun seringkali merupakan penumbangan budaya mapan.
Kumpulan cerpen itu telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh Dr. IM Hendrati, MA, dosen Sastra Inggris Undip, dan putranya, Kristian Tamtomo. Children Sharpening The Knife, salah satu judul cerpen Triyanto yang diterjemahkan dari “Anak-Anak Mengasah Pisau”, disinetronkan oleh sutradara kawakan Dedi Setiadi. Cerpen ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga kecil yang hidup di daerah belakang Stasiun Tawang Semarang, yang isinya banyak pelacur dan gali.
Cerpen ini pula yang telah memberi inspirasi para seniman Galeri Langgeng di Yogyakarta untuk menggelar pameran lukisan tentang kisah dalam cerpen itu. Tak hanya itu, cerpen ini juga dipentaskan oleh Teater Closed, teater mandiri di kota Surakarta. Itulah sebabnya cerpen ini memberikan banyak kesan baginya. “Ternyata cerpen saya bisa jadi inspirasi bagi orang lain,” tuturnya.
TRIYANTO Triwikromo yang bernama asli Triyanto ini, lahir di Salatiga, 15 September 1964, 36 tahun silam. Triyanto kecil tumbuh dari keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang buruh pabrik Damatex, pabrik tekstil di Salatiga. Sementara, sang ibu sehari-hari menjajakan makanan kecil di depan kantor pegadaian yang terletak tak begitu jauh dari tempat tinggalnya, sekitar 10 menit dengan jalan kaki.
Bakat menulis Triyanto tak datang dari keluarga. Bakat itu tumbuh tumbuh semenjak ia duduk di bangku kelas dua SMP. Saat itu ia dipercaya menjadi pengurus majalah dinding di sekolahnya. Berawal dari membuat mading itulah rupanya ia mulai belajar menulis. ”Kadang kalau tak ada yang membantu membuat mading, saya yang buat sendiri semuanya, karena kebiasaan membuat itulah membuat saya harus belajar,” kenangnya.
Selepas SMP, ia melanjutkan pendidikannya ke SPG (Sekolah Pendidikan Guru). Menurutnya, masuk SPG dianggap baik di kalangan masyarakat saat itu. Selain itu, ia bisa langsung mengajar karena ada ikatan dinas. Alasan yang kedua inilah yang sebenarnya mendasari pilihannya. ”Saya harus masuk SPG karena keluarga sangat miskin dan saya bisa menjadi guru, jadi bisa langsung kerja,” akunya.
Setelah lulus dari SPG, ia mengajar selama setahun di SD Kalicacing Salatiga. Rupanya perkembangan menjadi lain. Begitu lulus SPG dan mengajar, ia pun melanjutkan pendidikannya di IKIP Semarang Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia (sekarang menjadi Universitas Negeri Semarang, Red). “Dengan catatan nanti saya akan tetap mengajar,” ujar ayah dari Primaera Restu Wingit Anjani, Lang Lang Gredarera Sanrez Adami, dan Ibrah Fastabiqi Bawana Mukti. Karenanya, pada waktu mahasiswa, ia mengajar drama di SMP Gisik Brono. Tapi, nasib berkata lain. Ketika mengajar di sekolah itu, kepala sekolahnya tidak suka cara ia mengajar sebab kelas yang diajarnya sering membuat gaduh. Menurutnya, praktek drama dan puisi memancing keaktifan siswanya, hingga seringkali membuat kelas ramai.
“Rupa-rupanya dunia pendidikan tidak menerima saya. Ternyata teori-teori pembaharuan berbenturan dengan guru-guru yang lama,” ungkapnya mengenang masa lalu.
Teori-teori pembaharuan itu adalah teori cara mengajar yang aktif. “Ada dosen saya yang pinter, pak Ristiono namanya. Dia mengajarkan kami bagaimana mengajar dengan cara-cara yang aktif. Teori itu saya coba terapkan di tempat saya mengajar.”
Sebelum mengundurkan diri, ia menemui kepala sekolah. ”Pak nilai deduktif metodik saya A. Saya mengajar seperti ini secara teoritik ada, tetapi kalau saya tidak diperbolehkan mengajar, ya silakan,” ungkapnya waktu itu, kesal.
Setelah berhenti mengajar, setahun berikutnya, tahun 1988, ia mulai serius menulis dan dipercaya menganalisis puisi tiap bulannya di Harian Wawasan. Di tahun berikutnya, 1989, ia menjadi penyair terbaik Indonesia versi Gadis dengan sajak Perdamaiannya “Sajak Membaca Kepak Sayap Merpati”. Mulai saat itulah ia aktif di Suara Merdeka. ”Waktu itu Suara Merdeka meminta saya sebagai kontributor, secara resmi saya diterima di sana baru tahun 2000,” ujarnya.
Sebenanrnya, ia mulai menulis sejak duduk di bangku SMA. Namun, baru dipublikasikan sejak tahun 1986. Itu pun karena dicuri dan dikirimkan oleh teman kuliahnya, tapi tetap atas namanya. Waktu itu, ia belum berkeinginan untuk mengirimkan karyanya. Bahkan, ia lupa karya pertamanya yang dipublikasikan. “Saya lupa judulnya, dimuat di Suara Karya kalau tidak salah,” tuturnya.
INSPIRASI menulis Triyanto bisa datang dari hal apapun. Tak jarang inspirasi itu datang tiba-tiba. ”Dari kehidupan, dari apapun yang menggetarkan saya. Dari orang-orang, bukan penderitaan saja tapi keromantisan, keindahan orang, peristiwa-peristiwa yang menyentuh bisa jadi inspirasi,” ujarnya.
Pernah suatu ketika inspirasinya datang saat ia menyetir, atau saat ia jalan-jalan ke luar negeri. ”Waktu saya jalan-jalan di luar negeri, di Sidney, saya melihat dua orang lelaki berciuman mesra dan indah, karena saya jijik saya ganti perempuan dengan perempuan dan menginspirasi cerpen “Ikan Asing dari Weipa-Nappranum,” ujarnya.
Lain lagi ketika ia sedang berhaji di Tanah suci, Arab Saudi. Seperti saat jalan-jalan di dekat makam Balqi. Triyanto melihat seorang ibu dan anaknya yang ingin sekali mendekati makam. Namun dalam tradisi Arab, perempuan tak boleh masuk makam. Dari situlah tercetus cerpen “Mata Sunyi Perempuan Takroni”.
”Saya mencari dan studi dulu tentang masyarakat Takroni, jadi tidak melulu imajinasi,” ujarnya menjelaskan bagaimana ia menyelesaikan cerpen itu.
Lama penyelesaian tiap cerpen berbeda-beda. Ada yang sangat gampang, semalam jadi. Ada pula yang bertahun-tahun karena kesibukan. Inspirasinya juga datang dari hasil pencariannya, tak hanya menunggu. ”Saya bukan orang yang suka menuggu. Lebih baik looking for, mencari. Menunggu bikin orang males. Kadang-kadang dalam menunggu itu saya sedang mencari,” ujarnya.
Dalam setiap karyanya, ia tidak monoton mengupas persoalan ketertindasan perempuan seperti yang seringkali dilontarkan oleh pembaca atas karyanya. “Tidak semuanya perempuan, tetapi orang yang tertindas. Dan kebanyakan yang tertindas itu juga perempuan. Ada lelaki yang kalah, perempuan perkasa, perempuan yang menyiksa perempuan lain….” ujarnya.
Cerpen-cerpen lainnya yang dimuat di berbagai media adalah “Tujuh Belas Agustus Tanpa Tahun” (1991), “Labirin Kesunyian” (1992), “Litani Kebinasaan” (1993), “Ninabobo Televisi” (1996), “Cinta tak Mati-mati” (1997), “Masuklah Ke Telingaku, Ayah” (1999), “Cermin Pasir dan Rahim Api” (2002), “Sayap Anjing” (2003), “Malam Sepasang Lampion” (2004), dan masih banyak lagi. Diantaranya, sudah tersusun dalam buku kumpulan cerpen.
Mantan Redaktur Nuansa (Tabloid mahasiswa UNNES, Red) ini, memandang menulis sebagai tempatnya berefleksi, merenung, dan mengekpresikan keinginan-keinginan yang tak bisa diungkapkannya dalam kehidupan di masyarakat. Dan pada akhirnya, publiklah yang akan menilai. Ia juga tidak pernah menghitung-hitung berapa pesan yang sampai pada masyarakat, yang penting ia berharap masyarakat menghayatinya. “Biarkan pembaca menemukan makna itu,” ujarnya.
Menulis adalah tempat ia berefleksi dan baginya tidak sederhana. Bercakap-cakap dengan diri sendiri merupakan jalinan yang sangat kompleks.
“Bagi saya, bercakap-cakap dengan diri sendiri tidak akan menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Mending saya tulis,” ujarnya.
Motivasi menulisnya, karena ia ingin menghilangkan ‘pikiran- pikiran pengganggu’, yaitu segala pikiran atau perasaan yang mengganggu apabila itu tidak ia munculkan dalam tulisan. Dalam menulis, buku-buku yang ia baca menjadi pengaruh penting dalam proses kreatifnya.
“Semua bacaan mempengaruhi saya. Saya hidup di lingkungan yang gemar membaca,” ungkapnya.
Dalam pendidikan putra-putrinya, tak ada paksaan untuk mengikuti jejaknya. Walaupun saat ini putri sulungnya mengambil jurusan yang sama sewaktu ia kuliah, yaitu Sastra Indonesia di Universitas Diponegoro.
“Dia masuk Sastra atas keinginannya sendiri, biarkan dia menemukan dirinya sendiri,” tuturnya.
Ia berharap anaknya mungkin bisa menjadi kritikus sastra, karena ia tidak menjadi kritikus sastra.
“....ya kalo bisa, kalo nggak bisa ya biarin...” ujarnya ketika mengakhiri pembicaraan kami di sela perkuliahan S2 yang tengah ia ikuti di Fakultas Sastra, Universitas Diponegoro.
Tak salah bila Triyanto telah memilih jalan hidupnya sebagai seorang penulis meski harus melepaskan pekerjaannya sebagai guru. Pilihannya itu kini membawa kemenangan.****
*Dipublikasikan di taboid Hawe Pos edisi 12/Mei/2005
**Reporter Hawe Pos
